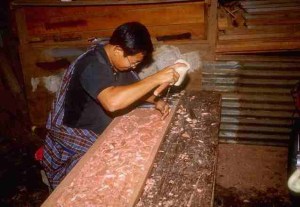sistem kekerabatan seyogianya dianut menurut garis keturunan bapak. Akan tetapi, masyarakat
dikenal sebagai kelompok masyarakat yang menganut garis keturunan menurut kaum ibu. "Keanehan" sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat
ini merupakan salah satu daya tarik untuk membicarakannya.
3. Daerah Rantau
Rusli Amran melihat perbedaan antara daerah Darat dan Rantau dahulunya hanya sebatas pada sistem kepemimpinan seperti yang termaktub dalam tambo. Kedudukan raja di daerah Rantau berada di bawah kepemimpinan penguasa di daerah Darat. Akan tetapi, perbedaan daerah Darat dan Rantau semakin meluas setelah terjadi "persinggungan" dengan dunia luar. Wilayah Rantau, terutama kota Padang, merupakan daerah pelabuhan yang merupakan "primadona" yang selalu diperebutkan oleh berbagai kekuasaan agar bisa menguasai perdagangan lada. Pada waktu Portugis menguasai daerah Rantau, pengaruh Portugis masuk dalam tatanan kehidupan masyarakat Rantau. Ketika daerah Rantau (kota Padang) dikuasai oleh para pedagang Aceh, warna Aceh ikut menyemarakkan kehidupan masyarakat daerah Rantau. Selanjutnya, pengaruh Belanda ikut mewarnai tatanan kehidupan masyarakat kota Padang ketika Daerah Rantau berada di bawah kekuasaan Belanda. Kekuasaan yang silih berganti di daerah Rantau menyebabkan kebudayaan yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakatnya menjadi beraneka ragam dengan perbedaan yang cukup kentara dengan daerah Luhak nan Tigo atau Darat (Navis, 1984:104).
Seorang laki-laki di kota Padang berhak mendapat dua warisan sekaligus, yaitu dari pihak ibu dan dari pihak ayah.
Harta warisan mereka terima dari pihak ibu, sedangkan gelar pusaka mereka terima dari pihak ayah (kadang-kadang ada juga dari pihak ibu).
Di samping itu, perbedaan lain antara daerah Darat dan Rantau terletak pada penerapan strata sosial masyarakat.
Terutama di kota Padang, bangsawan laki-laki menggunakan gelar "sutan"di depan namanya dan bangsawan perempuan mengunakan gelar "puti" atau "siti".
Mamak dan Ninik Mamak dalam Sistem Kemasyarakatan
Minangkabau
4.1 Mamak
Sutan Takdir Alisyahbana melihat ciri utama dari masyarakat
Minangkabau adalah adanya keterikatan orang
Minangkabau pada ibunya dan rumah serta pusaka keturunan ibunya. Kehidupan perasaannya berputar sekitar rumah ibunya, sedangkan perhubungan perasaan dengan ayahnya sangat dangkal (1983:20).
Pendapat itu memperlihatkan bahwa seseorang itu lebih ditegaskan sebagai anak seorang ibu dan seolah-olah mengingkari bahwa seseorang itu anak dari ayahnya.
Alasan itulah yang "mungkin" menyebabkan masyarakat
Minangkabau diklasifikasikan ke dalam masyarakat yang bersistem matrilineal (Muhardi, 1989:18).
Orang
Minangkabau sendiri tidak pernah menamakan susunan masyarakatnya sebagai masyarakat berketurunan ibu. Mereka menamakan sistem keturunannya menurut "kaum ibu". Seorang anak di
Minangkabau adalah keponakan dari mamaknya (saudara pria dari pihak ibu). Seseorang disebut tidak dengan mengutamakan "anak ibunya" (Nasroen, 1971:15). Sistem adat
Minangkabau seperti itu tercermin dalam ungkapan "kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke musyawarah, musyawarah beraja kepada alur dan patut[1]) yang berdiri dengan sendirinya". Ungkapan itu memperlihat bahwa seorang mamak sangat besar artinya bagi kemenakannya.
Kaitan erat antara mamak dan kemenakan tertuang dalam tugas dan tanggung jawab seorang mamak. Seorang mamak berfungsi sebagai pembina dan pembimbing anggota-anggota keluarga garis ibu yang terdekat.
Tugasnya adalah "mengapungkan" artinya memelihara, membina, memimpin kehidupan dan kebahagiaan jasmaniah dan rohaniah kemenakan-kemenakannya dari seluruh keluarganya (Mansoer, 1970:8). Meskipun seorang mamak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kemenakan, Umar Junus (1976:248) mengemukakan bahwa generasi yang di atas mamak ikut juga memikul tanggung jawab tersebut.
Untuk melibatkan generasi yang lebih tua digunakan istilah "ninik mamak".
Pembentukan kepribadian setiap warga
Minangkabau dititikberatkan atau bersandar sepenuhnya pada mamak dan ninik mamaknya.
Sebagai akibatnya, tingkah laku seseorang secara langsung dikaitkan dengan kemampuan atau ketidakmampuan mamaknya dalam mendidik atau membina kemenakannya. Mamak akan merasa malu atau sebaliknya bangga dengan kemenakannya (Muhardi, 1989:19).
Pada zaman dahulu, lembaga pendidikan yang digunakan seorang mamak untuk mendidik dan membina kemenakannnya adalah "surau". Oleh karena itu, seorang anak laki-laki yang telah berumur sepuluh tahun mulai menjalani kehidupan surau sampai dia dewasa atau berumah tangga. Ia akan menerima bimbingan dari mamak dan ninik mamaknya, menyangkut persoalan spritual dan material. Pembinaan itu berlangsung pada malam hari karena waktu siang hari digunakan untuk mencari nafkah sebagai bentuk pertanggungjawaban mamak sebagai seorang ayah (Muhardi, 1989:19).
Pendidikan yang diterima di surau meliputi tiga materi pokok. Ketiga materi yang diajarkan itu adalah
(1) pendidikan agama yang berlangsung setelah Magrib sampai Isya dengan materi menyangkut peribadatan seperti sembahyang dan pendalaman ajaran agama,
(2) pendidikan adat-istiadat meliputi pelajaran tentang pidato adat, seluk-beluk adat, sistem kemasyarakatan, serta hak dan kewajiban seorang menurut adat, dan
(3) pendidikan ketrampilan yang meliputi ketrampilan menganalisis kegiatan sehari-hari dan ketrampilan
 bela
bela diri pencak silat.
Kehidupan surau membiasakan seorang anak laki-laki hidup secara bersama dan bergaul sesama besar di bawah bimbingan tetua kampung. Dampak dari kehidupan surau ini, menurut Alisyahbana (1983:21) terlihat dari adanya kebebasan yang lebih dimiliki oleh laki-laki
Minangkabau daripada kebebasan yang dimiliki oleh laki-laki dari sistem kekerabatan lainnya. Faktor lamanya terlepas dari kungkungan dan penguasaan orang tua serta kebersamaan dengan teman sebaya memungkinkan munculnya kebebasan tersebut. Saling pengaruh-mempengaruhi antara teman sebaya memberikan kepercayaan atas diri sendiri yang besar bagi laki-laki
Minangkabau. Kebiasaan yang ditanamkan dalam menghadapi orang lain sebagai sesama sebaya menjadikan laki-laki
Minangkabau itu bebas dan mempunyai sikap demokratis.
Keadaan seperti itu didukung pula oleh hubungan dengan guru yang mengajar atau yang memimpin mereka lebih rasional daripada hubungan dengan ayah yang lebih cenderung memperlihatkan kekuasaannya atas anaknya (Muhardi, 1989:20).
Inisiatif ke segala penjuru berkembang karena kurang mendapatkan halangan dari orang tua yang sering mengekang dan menentukan segala-galanya. Pikiran dan insiatif dapat dengan bebas berkembang dalam suasana pertukaran pikiran dan perdebatan yang demokratis sehingga sesungguhnya salah satu ciri orang
Minangkabau di samping kepercayaannya terhadap diri sendiri adalah keluwesan dalam mengemukakan pendapat. Kelancaran menggunakan bahasa dalam mengemukakan pikirannya memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dalam berbagai organisasi politik, ekonomi, agama, dan lain-lain. Kepribadian orang
Minangkabau seperti dijelaskan di atas, di samping bersumber dari kebiasaan hidup secara komunal yang mendapat latihan di surau, juga karena falsafah adatnya yang memberi peluang untuk mengajarkan kebebasan tersebut, yaitu
alam terkembang jadi guru.
Dalam falsafah
alam terkembang jadi guru terkandung berbagai ajaran yang dapat ditafsirkan. Antara lain adalah bahwa kedudukan setiap orang atau setiap kelompok adalah sama dengan yang lain. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok bangsa. Seperti air, api, tanah, dan angin yang berkedudukan sama dan tak dapat saling menghancurkan. Adanya kesamaan kedudukan dalam tatanan masyarakat memberi peluang pada orang
Minangkabau untuk saling berlomba demi mengangkat martabat dan harga diri masing-masing, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok atau wangsa, agar sama dengan orang lain (Navis, 1984:59--60).
Kehidupan surau memberi kesempatan untuk berlomba demi menaikkan harkat dan harga diri pribadi dan pembinaan kehidupan komunal secara bersama-sama. Eksistensi individu dihargai dan dihormati dalam batas-batas kebersamaan. Mamangan[1]) adat "lamak di awak katuju di
 urang
urang" (enak bagi kita, enak pula bagi orang lain) adalah pencerminan bahwa seseorang itu dapat berusaha apa saja untuk kepentingan dirinya sepanjang tidak merugikan kepentingan orang lain. Jadi, yang menjadi prinsip hidup adalah keseimbangan antara kehidupan individu dan kehidupan masyarakat.
Persesuaian sikap antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama dapat terwujud jika penafsiran falsafah "alam terkembang jadi guru" tertuju pada sikap sikap seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan harkat serta martabatnya, tetapi tidak merusak atau mengorbankan harga diri orang lain. Kewajiban seseorang berdasarkan falsafah "alam terkembang menjadi guru" menurut Nasroen adalah
(1) seseorang mempunyai kewajiban terhadap leluhur, nenek moyang, diri sendiri serta masyarakat pada waktu sekarang, dan anak cucu yang akan datang,
(2) budilah yang menjadi dasar dan ikatan dalam menjalani kehidupan dan dalam menjalankan tugas dalam kebersamaannya,
(3) seseorang mempunyai kewajiban terhadap sesama seperti masyarakat, orang kampung yang harus dipertenggangkan, dan kewajiban terhadap penjagaan nagari agar jangan sampai binasa,
(4) perasaan malu merupakan suatu dorongan untuk maju, baik secara perseorangan maupun secara bersama, demi mengejar ketertinggalan dari orang lain. Perasaan malu itu juga mempunyai unsur pedagogis bagi seseorang atau suatu pergaulan hidup, dan
(5) seseorang mempunyai kewajiban untuk berbuat baik agar meninggalkan jasa-jasa dan nama baik (1971:59).
Kedinamisan dan kepercayaan terhadap diri sendiri akibat sistem pendidikan surau yang bersifat komunal tidak hanya dimiliki oleh laki-laki semata, tetapi juga menjiwai watak perempuannya. Alisyahbana menggambarkan bahwa perempuan
Minangkabau mempunyai kepercayaan atas dirinya sehingga mereka tidak bergantung sepenuhnya pada suami yang dijemputnya. Dalam kehidupannya, perempuan
Minangkabau biasa bekerja dan bertanggung jawab atas anak, rumah, dan tanah yang ikut dimilikinya serta dikerjakan dan dinikmatinya. Kepada suami yang dijemputnya, perempuan
Minangkabau tidak merasa berhutang budi dan tidak bergantung. Dalam perbuatannya, mereka bebas.
Perempuan
Minangkabau percaya pada dirinya, aktif dan penuh inisiatif dalam kehidupan ekonomi, politik, agama, seni, dan lain-lain (1983:20--21).
Kepercayaan terhadap diri sendiri bagi perempuan
Minangkabau ditunjang oleh penguasaan mereka terhadap harta pusaka.
Harta Pusaka di
Minangkabau diturunkan melalui garis ibu, yang berhak menerimanya adalah anggota keluarga yang perempuan. Anggota keluarga yang laki-laki dari sebuah keluarga matrilineal sebenarnya tidak berhak menerima harta pusaka.
Mereka hanya berkewajiban untuk menjaga harta pusaka itu agar tidak hilang dan mengusahakannya agar bermanfaat bagi kaum kerabatnya (Junus, 1976:253).
Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, seorang
Minangkabau dalam pendidikannya bergantung pada mamaknya, seorang wanita mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan seorang mamak berkewajiban membina keluarganya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kedudukan seorang suami atau seorang ayah dalam suatu keluarga
Minangkabau? Secara adat kedudukan seorang suami atau ayah dalam keluarga
Minangkabau termasuk keluarga lain dari keluarga istri dan anaknya, sama halnya dengan seorang anak dari seorang laki-laki akan termasuk keluarga lain dari ayahnya (Junus, 1976:247). Dan, seorang ayah berfungsi sebagai mamak dari keluarganya.
Ia juga mempunyai kemenakan. Jadi, seorang laki-laki
Minangkabau berfungsi ganda, yaitu mamak dari kemenakannya dan ayah dari anak-anaknya.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, tugas seorang laki-laki
Minangkabau termaktub dalam ungkapan "anak dipangku dan kemenakan dibimbing".
Jika dihinaprenungkan, tugas seorang laki-laki
Minangkabau tersebut pada prinsipnya mendahulukan kepentingan anak daripada kemenakan. Dengan kata lain, fungsi seorang ayah lebih utama daripada fungsi seorang mamak. Kebutuhan utama seorang anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Dalam hal ini, seorang anak
Minangkabau mendapat dua pengayom sekaligus, dari ayah dan dari mamak.
Adat mengumpamakan bahwa mamak itu sebagai payung yang dipakai ketika hujan, sedangkan ayah adalah payung yang dipakai ketika panas.
Sebagai akibat logis dari fungsi seorang pria
Minangkabau sebagai mamak dan sekaligus sebagai ayah, tidak aneh jika dia sedapat mungkin mengusahakan perkawinan diantara anak dan kemenakannya. Seperti yang dijelaskan Junus (1976:248) bahwa pada zaman dahulu, seseorang laki-laki dianjurkan kawin dengan anak perempuan mamaknya atau gadis-gadis yang dapat digolongkan demikian, misalnya kawin dengan kemenakan perempuan ayah (anak saudara perempuan). Orang juga boleh kawin dengan saudara perempuan suami dari saudaranya sendiri.
Namun, pada prinsipnya perkawinan antara penduduk nagari yang satu dengan nagari yang lain jarang terjadi. Perkawinan di
Minangkabau pada umumnya bersifat eksogami menurut suku, endogami menurut nagari. Oleh karena itu, ikatan dan hubungan darah antara penduduk senagari erat sekali. Lazimnya, penduduk yang satu masih memiliki hubungan keluarga dengan penduduk yang lain (Mansoer, 1970:18). Dengan demikian, sistem perkawinan ini lebih memperkokoh sistem kekerabatan yang ditumbuhkan dalam kebersamaan "surau". Hal itu menyebabkan seseorang itu lebih merasa terikat lagi dengan kekerabatan kebersamaan antara sesama penduduk nagari.
Karena sistem kekerabatan itu, umumnya kesetiaan orang
Minangkabau terutama dipusatkan pada keluarga menurut urutan dan gradasi perut (kandung), kaum, suku, kampung dan nagari, jarang sekali sampai ke Luhaknya (Mansoer, 1970:7).
Masing-masing orang
Minangkabau hanya mempunyai kesetiaan kepada nagari mereka sendiri dan tidak kepada seluruh
Minangkabau.
Seseorang dari nagari
 a
a yang tinggal di nagari B akan dianggap orang asing (Junus, 1976:242). Kelanjutannya ialah bahwa orang
Minangkabau tidak akan pernah hidup sebatang kara dan terlantar. Di mana pun berada, dia selalu dapat menjumpai keluarga sekaum, sepersukuan atau belahan, senagari yang secara moril berkewajiban menampung anggota sekaum, sepersukuan, belahan, dan senagarinya (Mansoer, 1970:6).
Dalam masyarakat
Minangkabau dikenal jenjang ikatan kemasyarakatan, yaitu
(1) keluarga,
(2) kaum,
(3) suku,
(4) nagari,
(5) luhak, dan
Dengan kata lain, alam
Minangkabau mempunyai tiga luhak (Tanah Datar, Agam, dan Lima Puluh Kota). Masing-masing Luhak terdiri atas beberapa nagari, sedangkan di dalam nagari terhimpun beberapa suku. Sementara itu, suku terdiri atas beberapa kaum sebagai kumpulan dari beberapa keluarga. Keluarga, dalam pengertian ini, adalah anggota sedarah karena berasal dari satu ibu, dari satu nenek, dan dari suku yang sama. Mansoer mengelompokkan keluarga ini atas tiga bahagian, yaitu
· keluarga sejengkal,
· keluarga sehasta, dan
· keluarga sedepa (1970:6).
Suku secara harfiah berarti kaki. Sesuku mengandung makna "sekaki", seperempat bagian dari seekor hewan ternak. Induk suku menurut adat Datuk Perpatih Nan Sabatang dan adat Datuk Ketumanggungan terdiri atas empat kelompok besar, yaitu
(1) Bodi,
(2) Caniago,
(3) Koto, dan
(4) Piliang.
Tiap-tiap induk suku dalam perjalanan sejarah terbagi-bagi menjadi anak suku, disebut dengan jurai yang berjumlah 128 jurai. Anggota induk suku dan jurainya hidup tersebar di seluruh pelosok alam
Minangkabau. Setiap orang
Minangkabau mengetahui apa sukunya yang diterimanya dari pihak keluarga ibu (Mansoer, 1970:5). Anggota sesuku merupakan perluasan dari sebuah keluarga yang berkembang menjadi kaum.
Kemudian, kaum berkembang pula menjadi berbagai bentuk suku. Dengan demikian, sebuah suku pada mulanya berasal dari satu keluarga. Hal itulah yang menjadi landasan atas pelarangan bagi orang
Minangkabau untuk kawin dengan orang sepersukuan.
4.2 Ninik Mamak (Penghulu)
Pada dasarnya, setiap laki-laki
Minangkabau berkedudukan sebagai mamak dalam keluarganya. Di samping itu, dia juga berpotensi untuk menempati kedudukan ninik mamak. Ninik mamak dalam pengertian ini adalah pimpinan yang dipilih atas kesepakatan kaum yaitu penghulu yang sering disebut dengan "datuk". Jika dalam kaum yang menjadi pimpinannya adalah ninik mamak (anggota laki-laki dewasa), suku dipimpin oleh seorang penghulu yang biasa disebut "datuk". Penghulu dipilih diantara anggota suku yang bersangkutan. Sebagaimana mamak berfungsi sebagai pembimbing dan pembina dalam keluarganya, penghulu berfungsi juga sebagai pembimbing dan pembina dalam sukunya. Dalam sebuah suku, biasanya juga dipilih seorang atau beberapa datuk muda yang disebut penghulu penongkat. Penghulu penongkat bertugas membantu atau memberikan kekuatan tenaga pada penghulu yang sudah tua.
Ia akan bertindak mewakili penghulu kaum atau suku, baik dalam berurusan dengan persoalan di dalam kaum atau sukunya maupun di luar suku dan kaumnya.
Kedudukan penghulu menurut adat adalah "didahulukan selangkah ditinggikan seranting"[1]) dari yang lainnya. Dalam pengertian ini, jarak antara yang memimpin dan yang dipimpin terletak pada penempatan posisi si pemimpin. Sebagai seorang yang dipilih didahulu selangkah dan ditinggikan seranting, seorang penghulu harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Antara lain, seorang penghulu harus beralam lapang dan berjiwa besar serta bijaksana dan "lubuk akal lautan budi"[1]) (Hasan, 1988:119). Setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat yang bermacam coraknya harus diselesaikannya dengan bijaksana. Lambang kepemimpinan penghulu itu adalah sebagai beringin di tengah padang yang cenderung ke arah memberikan perlindungan pada orang lain dan bukan merugikan orang lain. Karena rindangnya pohon beringin itu, dia dimuliakan karena menambah semarak dan melindungi tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jika terjadi persengketaan dalam kaumnya, penghulu harus menyelesaikannya dengan musyawarah sehingga putusan dapat diterima oleh semua pihak. Kalau seorang kemenakan memandang mamak sebagai raja, mamak memandang penghululah sebagai raja.
Sementara itu, penghulu memandang musyawarah sebagai raja, sedangkan musyawarah menempat alur dan patut sebagai yang harus dipedomani.
Mengingat pentingnya fungsi dan peranan penghulu dalam kehidupan masyarakat
Minangkabau, penghulu ditentukan atau dipilih tidak dari sembarang orang. Dengan kata lain, tidak semua anggota laki-laki dalam satu kaum dapat diangkat jadi penghulu meskipun mereka berpotensi untuk dipilih. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa memangku jabatan penghulu tersebut. Seseorang yang diangkat menjadi penghulu seyogianya memenuhi beberapa kriteria. Pertama, dia harus mengutamakan kebenaran, lurus, jujur, bertanggung jawab, dan berani mengemukakan yang benar itu benar. Kedua, seorang calon penghulu harus cerdas, berpendidikan, dan berpengetahuan. Ketiga, seorang calon penghulu harus dapat dipercaya, terjauh dari sifat buruk seperti penipu, pendusta, pembohong, penjudi, peminum, dan pemboros.
Keempat, seorang calon penghulu harus fasih berbicara demi meyakinkan orang lain akan maksud yang baik dalam suatu rencana yang dipunyai dan pekerjaan yang akan dilaksanakan demi perbaikan segala bidang masyarakat (Hakimi, 1984:10).
Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan. Larangan dan pantangan tersebut adalah menghindari perbuatan yang bertentangan dengan agama dan adat serta perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepenghuluannya. Sementara itu, perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat seorang penghulu termaktub dalam ungkapan berikut ini.
"Hilie malonjak, mudiak mangacau. Kiri kanan mamacah parang. Mangusuik alam nan salasai, mangaruah aia nan janiah.
Bak paham kambiang dek ulek karano miskin pado budi.
Barundiang bak
 sarasah
sarasah tajun karano takabua dalam hati. Mangubahi lahie
 jo
jo batin, maninggakan sidiq jo tabalie, mamakai cabuah sio-sio, kato nan lalu lalang sajo, bak caro
 mambaka
mambaka buluah, rundiang bak marandang kacang sabab lidah tak batulang (Hakimi, 1984 :22--23). (hilir melonjak, mudik mengacau. Kiri kanan menimbulkan masalah.
Mengusut persoalan yang telah selesai dan memperkeruh air yang telah jernih. Memiliki paham seperti kambing dihinggapi ulat karena miskin budi. Berbicara seperti air terjun karena memiliki sifat sombong, mengubah yang lahir menjadi batin, meninggalkan sidiq dan amanah, mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, berkata semaunya saja. Seperti membakar buluh, berkata seperti merandang kacang karena lidah tak bertulang).
Intinya, seorang penghulu harus menghindari pekerjaan dan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti sirik, perbuatan maksiat, takabur, pemarah, berdusta, menipu, mencuri, mabuk, berjudi, munafik, dan meninggalkan rukun islam yang lima. Sementara itu, pekerjaan dan sifat yang dilarang oleh adat adalah pekerjaan yang menyimpang dari alur dan patut seperti perbutan yang memecah belah orang berkeluarga, menimbulkan huru-hara, pemalas, mungkir janji. Di samping itu, seorang penghulu seyogianya menghindari pekerjaan yang sumbang menurut pandangan adat seperti dalam berpakaian, berkata-kata, bertingkah, dan bergaul (Hakimi, 1984 :23).
Sebagaimana telah diungkapkan terdahulu, seorang penghulu memiliki keterkaitan dengan kaum dan nagarinya. Sementara itu, Nagari merupakan kediaman utama dan dianggap sebagai pusat aktivitas sebuah desa. Daerah nagari ditentukan oleh adanya mesjid, sebuah balai adat, dan tempat untuk pasar sekali atau dua kali seminggu (Junus, 1976:243). Pepatah adat menyebutkan persyaratan sebuah nagari adalah "babalai bamusajik, balabuah bagalanggang, batapian tampek mandi."
Artinya, sebuah daerah baru dapat dikatakan sebuah nagari jika daerah tersebut memiliki balai adat tempat bermusyawarah, mempunyai mesjid tempat beribadah, mempunyai jalan untuk kepentingan perhubungan, mempunyai gelanggang untuk berolah raga dan bermain, dan memiliki tepian tempat mandi.
Nagari merupakan federasi genealogis, kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan ikatan kekeluargaan menurut pertalian keturunan yang sangat erat, dari beberapa suku. Nagari mempunyai wilayah sendiri dengan batas-batas alam yang jelas dan mempunyai pemerintah yang berwibawa dan ditaati oleh penduduk nagari. Pemerintahan nagari dilakukan oleh Dewan Kerapatan Adat, yang anggota-anggotanya terdiri atas penghulu-penghulu andiko[1]) sebagai wakil keluarga, kaum atau suku. Pada dasarnya, nagari adalah "republik otonom" yang dengan sesamanya membentuk federasi longgar. Federasi longgar dari "federasi republik nagari" dinamakan "luhak" (Mansoer, 1970:15). Penggunaan istilah nagari mempunyai keragaman seperti koto, jorong, kampung, bandar, dan lain-lain. Penggunaan istilah yang beragam itu memperlihatkan bahwa masing-masing nagari memiliki otonomi dalam mengatur dirinya.
Secara formal, penghululah yang menjadi pemimpin di
Minangkabau. Mereka seolah-olah penguasa otonom karena memiliki daerah (nagari, sawah, dan ladang), rakyat (kemenakan anggota sukunya) yang mematuhi segala perintah yang dibuatnya. Akan tetapi, dalam sebuah suku biasanya dikenal pula tokoh-tokoh lain yang mempunyai peran. Mereka adalah "orang empat jenis". Orang empat jenis ini terdiri atas penghulu, imam, manti, dan hulubalang (dubalang). Diungkapkan dalam pepatah adat bahwa kata "penghulu kata penyelesai, kata imam kata hakekat". Tugas manti adalah menyampaikan keputusan penghulu dan hulubalang (dubalang) adalah pelaksana keputusan tersebut.
Umar Junus mengatakan bahwa kita tidak dapat mengatakan dengan jelas siapa yang menjadi pemimpin bagi suatu "paruik"[1]) karena setiap orang dewasa berhak dan tidak berhak menjadi pemimpin kaumnya. Perintah atau saran seseorang mungkin akan dilaksanakan oleh anggota keluarganya, tetapi ini tergantung pada wibawa dan kepribadian seseorang tersebut (1976:252). Seorang penghulu suku atau penghulu andiko juga tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Mereka lebih banyak dirasakan sebagai yang dituakan dan bertugas menjalankan sesuatu pekerjaan. Menjadi penghulu lebih banyak dirasakan sebagai mendapat tugas daripada mendapat hak. Hanya bila kepenghuluan ini dihubungkan dengan kekuasaan Belanda dahulu yang "mungkin" juga berlaku saat ini, barulah seorang penghulu tersebut mendapatkan kekuasaan (Junus, 1976: 252--253).
Penghulu yang duduk di Kerapatan Nagari disebut juga dengan "penghulu pucuk", "penghulu payung" atau "penghulu andiko". Dari sebutan tersebut terlihatlah tugas dan fungsi penghulu itu sebagai pemimpin masyarakat
Minangkabau.
Pucuk merupakan bahagian tertinggi yang bertunas terus karena itu menjamin kelanjutan hidup tanaman. Payung merupakan wadah tempat berlindung, baik dari sengatan matahari maupun dari siraman hujan.
Berdasarkan pengertian yang sering melekat pada kata penghulu itu, jelaslah tugas dan fungsi seorang penghulu: sebagai pemimipin yang memerintah yang sekaligus menjamin kelanjutan dan kesejahteraan anak dan kemenakan serta sebagai pelindung bagi kaumnya. Pepatah yang mengungkapkan sistem kepemimpinan masyarakat
Minangkabau--kemenakan beraja pada mamak, mamak beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut--mengimplikasikan bahwa fungsi penghulu itu sebagai tempat berlindung anak dan kemenakan. Namun, dia harus memerintah berdasarkan hasil mufakat dalam musyawarah.
Secara adat penghulu adalah pemimpin, tetapi kepemimpinan dalam keseluruhan sistem kemasyarakatan. Di samping penghulu, masih ada pemimpim yang disebut ulama dan cerdik pandai. Ketiga unsur tersebut dikenal dengan istilah "tali tiga sepilin" atau "tungku tiga sejarangan". Ketiga unsur tersebut secara bersama-sama memimpin masyarakat Minangkabau. Ulama memimpin dalam bidang keagamaan, sedangkan cerdik pandai memimpin dalam bidang kehidupan sosial-ekonomi serta pendidikan.
Garis pemisah yang tegas antara kepemimpinan itu seringkali sulit ditarik. Adakalanya, seseorang menyandang tugas sebagai penghulu dan ulama sekaligus. Sementara itu, kaum cerdik pandai banyak juga yang menjadi penghulu atau ulama. Namun, ketiganya--dilihat dari sebuah sistem--desebut sebagai pemimpin tergantung pada persoalan yang dihadapinya. Untuk menghadapi persoalan yang bersifat terpadu, dilakukanlah musyawarah untuk mencapai mufakat.
Permusyawaratan yang dilakukan oleh pemimpin atau pemuka masyarakat tidak berdasar pada suara mayoritas karena itu sistem "voting" suara tidak dikenal. Musyawarah untuk mencapai mufakat didasari azas seia-sekata serta kesepakatan. Hal itu tercermin dalam pepatah adat "
 Bulek
Bulek lah buliah digolongkan,
 picak
picak lah buliah dilayangkan" (jika bulat sudah boleh digolongkan dan kalau
 pipih
pipih sudah boleh dilayangkan), yaitu suatu kesepakatan telah memperoleh persetujuan bersama dan dapat dilaksanakan.
Untuk mencapai kesepakatan, musyawarah harus berpegang teguh pada prinsip berdasarkan alur dan patut. Penilaian alur dan patut disesuaikan dengan kondisi dan situasi waktu dan tempat, tidak selalu sama untuk segala zaman dan keadaan. Jadi, permusyawaratan adalah untuk mencari mana yang baik bagi penyelesaian suatu permasalahan dengan berpijak pada situasi dan kondisi yang tengah dihadapi (Mansoer, 1970:11).
Jika kata kehidupan yang terlahir berdasarkan sistem rasa kebersamaan untuk kepentingan bersama seperti itu dapat dipandang sebagai suatu tata demokrasi, posisi pemimpin--dalam masyarakat
Minangkabau--bukanlah sebagai penguasa yang dapat menentukan suatu keputusan (Navis, 1983:86). Seorang pemimpin seperti mamak atau penghulu sesungguhnya merupakan simbol, sedangkan yang menentukan segalanya adalah mufakat.
Mengingat bahwa kepemimpinan penghulu di tingkat nagari merupakan simbol, kepemimpinan raja
Minangkabau juga merupakan simbol. Alasannya karena alam Minangkabau merupakan federasi dari luhak yang sekaligus juga merupakan federasi dari beberapa nagari. Raja
Minangkabau bukanlah seorang tokoh politik seperti raja-raja di tanah Jawa. Mereka juga tidak merupakan lambang kesatuan dan persatuan bangsa seperti raja Inggris. Ia hanya seorang tokoh"sakral" atau "orang bertuah" yang hidup dari hasil tanahnya sendiri dan dari "bunga tanah" serta upeti dari daerah alam
Minangkabau, rantau dan pesisir yang pada hakekatnya lebih merupakan lambang daripada bukti pernyataan takluk dalam pengertian politis (Mansoer, 1970:23).
Selanjutnya, kiprah seorang penghulu (ninik mamak) dalam konsep adat dan kebudayaan
Minangkabau dapat dilihat dari perannya
(1) sebagai anggota masyarakat,
(2) sebagai mamak bagi kemenakannya,
(3) sebagai seorang suami bagi istrinya,
(4) sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya, dan
(5) sebagai pemimpin dalam nagari
(Hakimi, 1994:7).
5. Dinamika Masyarakat
Adat dan kebudayaan
Minangkabau membuka diri terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Hal itu setidaknya tersirat dari pepatah adat "sakali aie gadang, sakali tapian barubah" (sekali air besar, sekali tepian berrubah). Akan tetapi, perubahan-perubahan yang muncul tidak bersifat radikal, yaitu melenyapkan konsep-konsep yangsudah ada. Namun, lebih mengarah pada penyempurnaan. Akan tetapi, sekecil apapun perubahan-perubahan yang terjadi pasti menimbulkan riak-riak dalam masyarakat yang mungkin bermuara pada pelahiran berbagai konflik[1]). Sistem sosial dan kebudayaan
Minangkabau memberi peluang untuk kondisi semacam itu. Hal itu setidaknya dapat dipedomani dari adanya pepatah adat yang menyiratkan penyelesaian konflik "basilang kayu dalam tungku, makonyo api manyalo" (api baru bisa nyala dan membakar tumpukan kayu jika kayu-kayu tersebut dipersilangkan, tidak ditumpuk begitu saja). Artinya, suatu persoalan dapat dicarikan pemecahannya melalui suatu perdebatan terlebih dahulu. Akan tetapi, silang pendapat tersebut dimaksudkan semata-mata untuk mendapatkan solusi, bukan untuk menimbulkan disintegrasi.
Kondisi semacam itu sudah kelihatan pada sikap tokoh
Minangkabau tempo dulu yang telah berjasa menetapkan hukum adat
Minangkabau, yaitu Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan. Perdebatan antara kedua tokoh ini bermuara pada pelahiran sistem kelarasan di
Minangkabau. Dari persilangan pendapat antara kedua tokoh itu akhirnya
Minangkabau ditetapkan menjadi dua kelarasan. Kelarasan Datuk Perpatih nan Sabatang--Bodi-Caniago--mengutamakan demokrasi, tanpa membedakan kedudukan penghulu. Sementara itu, kelarasan Datuk Ketemanggungan-Koto-Piliang--menerapkan sistem gradasi yang membeda-bedakan kedudukan seorang penghulu. Pertentangan antara kedua tokoh tersebut sempat menimbulkan ketegangan, namun akhirnya bersatu dengan saling menghargai konsep masing-masing (Abdullah, 1966:6--7).
Berkembangnya dinamika masyarakat tidak terlepas dari pengaruh dalamdan dari luar masyarakat itu sendiri. Nasroen (1971:39) mengemukakan dialektika antara kedua kutub tersebut sudah lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat
Minangkabau.
Oleh karena itu,
Minangkabau sangat terbuka oleh berbagai pengaruh.
Persoalan modernisasi,[1]) misalnya, bukan lagi persoalan baru bagi masyarakat Minangkabau karena kemajuan pendidikan--sebagai salah satu aspek modernisasi tersebut--merupakan suatu hal yang telah lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Junus,1976:257). Modernisasi bagi masyarakat Minangkabau dimungkinkan oleh kondisi sosiokulturalnya. Sistem kemasyarakatan yang demokratis merupakan lahan yang subur untuk menerima dan menumbuhkan hal-hal yang baru. Budaya merantau merupakan sarana yang ampuh menjadi jembatan modernisasi dari rantau ke daerah Minangkabau. Modernisasi yang masuk melalui para perantau mengalami proses seleksi alami sebelum dibawa pulang ke daerah
Minangkabau oleh para perantau tersebut.
Seperti contoh dapat dikemukakan alasan fungsionaris Jong Sumatera Bond ketika membawa pergerakan itu ke kampung halamannya. Kehadiran Jong Sumatera Bond dimanfaatkan untuk mempertahankan adat dan agama. Tentu saja ini menyenang-kan. Kemudian, Jong Sumatera Bond berbicara tentang keharusan anggotanya berpengetahuan Barat meskipun tetap mempertahan jiwa Timur (Abdullah, 1983:148).
Modernisasi yang biasanya dikaitkan dengan pengaruh-pengaruh luar tidak aneh bagi masyarakat
Minangkabau karena rasionalisme yang menjadi landasan modernisasi telah dikenal sebelumnya. Adat yang berpola sistem musyawarah telah mengasah berkembangnya rasio. Pendidikan "surau" yang membiasakan belajar secara bersama adalah bibit dan wadah pengembangan rasio bagi masyarakat
Minangkabau. "hidup berakal, mati beriman" merupakan moto yang menyiratkan adanya peranan rasio di dalam kehidupan karena akal atau rasio digunakan untuk hidup, sedangkan iman dipersiapkan untuk menghadapi Ilahi (Muhardi, 1984:47).
Bahkan Van der Plas mengemukakan bahwa kaum intelek agama Islam di
Minangkabau dengan berjenis-jenis sekolahnya dan organisasinya adalah imbangan yang layak dari kaum intelek pendidikan Belanda yang banyak di Pulau Jawa (Alisyahbana, 1983:22). Islam dalam berakar di
Minangkabau dan dapat mencapai tingkat kemajuan yang tinggi. Agaknya, hal itu bukan disebabkan oleh Islamnya, tetapi mungkin sekali oleh watak orang
Minangkabau yang ditimbulkan oleh kaitannya dengan sistem matriaki.
Pada waktu kedatangan ajaran komunis, orang
Minangkabau pun menerimanya dengan kegairahan dan kesungguhan yang mungkin tidak kalah dengan sikap mereka terhadap agama Islam. Dari sekian daerah di Indonesia, daerah
Minangkabau termasuk daerah yang paling terbuka untuk dunia modern. Hal itu terbukti dengan banyaknya kaum intelek dan pemimpin modern yang berasal dari
Minangkabau (Alisyahbana, 1983:23).
Setiap pembaharuan yang masuk tetap melalui orang-orang
Minangkabau yang baru kembali dari rantau, baik dalam bentuk ajaran agama maupun ideologi lainnya. Pada waktu terjadi pembaharuan, saat itu pun terjadi konflik karena pada hakekatnya konflik ditimbulkan oleh adanya perbenturan pemikiran. Apakah konflik itu mencapai pertententangan fisik atau tidak, tetapi selalu diselesaikan dalam musyawarah. Hasil dari konsensus jelas menimbulkan pergeseran-pergeseran nilai-nilai lama yang dianut sebelumnya. Di sini, perlu pula ditegaskan bahwa tidak semua nilai-nilai pembaharuan dapat diterima oleh masyarakat
Minangkabau. Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa aliran ideologi atau agama tertentu mencoba masuk ke
Minangkabau ternyata tidak mendapat tempat di kalangan masyarakat
Minangkabau.
Jadi,
Minangkabau menerima pembaharuan. Akan tetapi, pembaharuan yang diterima adalah pembahruan yang telah lolos dari proses seleksi budayanya.
Dinamika masyarakat tersebut juga mempengaruhi fungsi mamak dan ninik mamak dalam tatanan kehidupan masyarakat
Minangkabau. Sebelum
Minangkabau bersinggungan dengan budaya luar, peran mamak dan ninik mamak sangat dominan dalam keluarga istri. Sistem pewarisan harta pusaka pada kemenakan menurut Djamaris (1996:23) menyebabkan semakin eratnya hubungan seorang mamak dengan keluarga ibunya.
Akan tetapi, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa peran seorang ayah dalam keluarga
Minangkabau semakin menonjol.
Akibat dinamika masyarakat yang terus berlangsung, keluarga-keluarga
Minangkabau tidak lagi menempati rumah adat, tetapi rumah yang hanya ditempati keluarga inti. Di samping itu, harta warisan tidak memadai lagi menghidupi para kemenakan karena pertambahan populasi kemenakan yang semakin tinggi. Konsekwensinya, sebuah keluarga beralih sepenuhnya menjadi tanggungan ayah. Peranan mamak dalam keluarga tersebut menjadi berkurang karena kewajiban yang dipikulkan pada mamak berpindah pada ayah. Dengan demikian, peran seorang ayah menjadi lebih dominan terhadap seorang anak daripada peran mamaknya.
6. Penutup
Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami Indonesia.komunitas
Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang kuat "menjunjung adat dan kebudayaan" nenek moyangnya. Akan tetapi, komunitas
Minangkabau juga dikenal sebagai insan-insan yang menjunjung tinggi prinsip "di mana bumi
 dipijak
dipijak, di sana langit dijunjung."
Kadang-kadang, perbenturan antara budaya ibu dan budaya tepatan tidak dapat dielakkan sepenuhnya oleh masyarakat
Minangkabau yang berada di perantauan.
Namun, di sisi lain, kondisi seperti itu sangat menguntungkan karena dapat memperkaya dinamika masyarakat
Minangkabau itu sendiri.
Sumber : <http://www.geocities.com/gurau_palanta/>




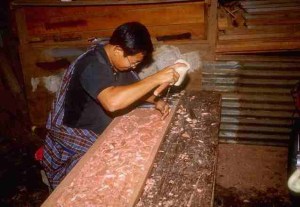


 Surau Sebagai Skriptorium Naskah Minangkabau
Surau Sebagai Skriptorium Naskah Minangkabau  Syekh Muhammad Jamil Jaho, Ulama Pembaru dari Minang
Syekh Muhammad Jamil Jaho, Ulama Pembaru dari Minang Sjech Jamaluddin
Sjech Jamaluddin